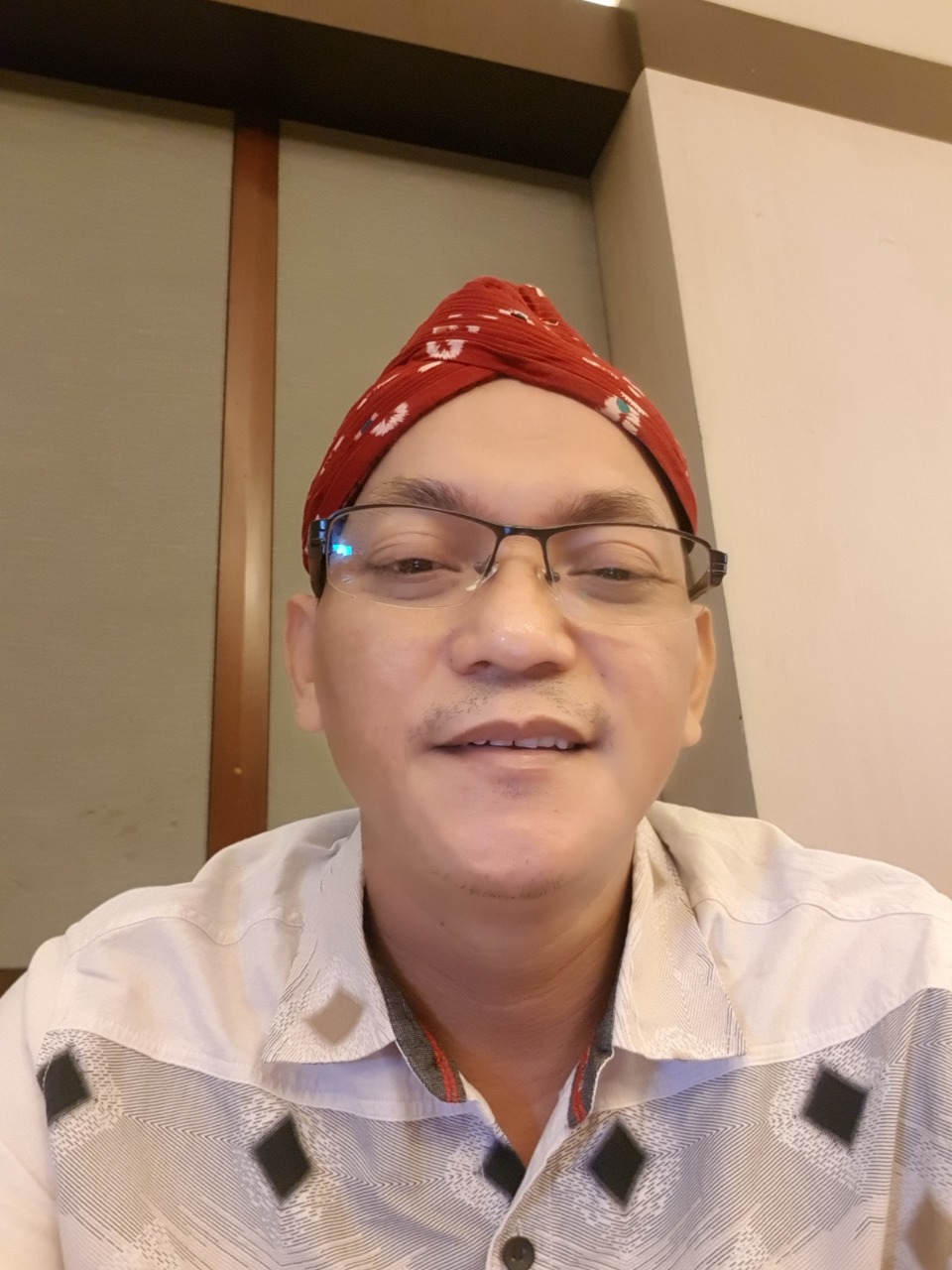Metaverse yang diawali dari novelnya Neal Stephenson -Snow Crasah yang difilmkan tahun 1992, menjadi awal mula pelarian seorang pengantar pizza bernama Hiro. Di dunia nyata Hiro bukan siapa-siapa. Dengan menggunakan kacamata realitas virtual (VR), Hiro seolah mewujudkan mimpinya untuk menjadi seseorang yang memiliki eksistensi dan kedaulatan. Eksistensi dan kedaulatan Hiro di dunia maya lebih kuat, dibanding eksistensinya di dunia nyata, yang tak berarti. Film The Matrix (1999) yang dilakoni Keanu Reeves, atau Ready Pleyer One (2018) yang dibintangi Tye Sheridan, menjadi contoh dari dunia metaverse.
Di metaverse, individu bisa memilih menjadi apapun, melalui avatarnya -pengganti identitas dan jati dirinya. Semua orang memiliki otoritas untuk menentukan apapun. Individu dalam metaverse mampu mewujudkan imaginasi yang tak mungkin dilakukan di dunia nyata. Metaverse menawarkan ideologi kebebasan, keterbukaan dan kedaulatan individu. Nasionalisme akan teronggok dipojok. Agama dan ideologi negara akan menjadi barang antik. Kewarganegaraan menjadi melar dan terbuka. Tak dipatok satu negara. Teritorial geografis menjadi selarik debu di kaca. Hingga bos Facebook, pun mendeklarasikan ganti nama “META”. “META” menjadi rahim negara global virtual. Dan presidennya adalah Mark Zuckerberg.
Entah, adakah moralitas dan agama atau ideologi Pancasila di metaverse? Sebab penduduk maya metaverse bisa berasal dari mana saja, yang bisa jadi tak kenal Pancasila. Bahkan di dunia nyata pun, di benak 272 juta rakyat Indonesia, Pancasila pun belum menapak. Mungkin Pancasila harus masuk juga ke Metaverse. Semakin berat tugas Romo Yudian Wahyudi. (*)
OLEH: Kang Marbawi